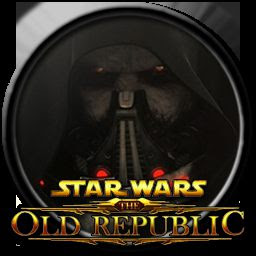NUZULUL
QUR'AN
“Bulan
Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang
haq dengan yang bathil)..” [al-Baqarah:185]
Frasa
awal ayat ini menjelaskan bahwa, al-Quran al-Karim telah diturunkan Allah Swt.
di bulan Ramadhan pada Lailatul Qadar. Al-Quran telah menyatakan hal ini
dengan sangat jelas.
“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada
suatu malam yang diberkahi..” [al-Dukhaan [44]:3]
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya
(al-Quran) pada malam kemuliaan (lailatul qadar].” [al-Qadr [97]:1]
Ali Al-Shabuniy menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “lail
mubaarakah” (malam yang diberkahi) adalah malam yang sangat agung dan
mulia, yaitu Lailatul Qadar di bulan yang penuh berkah (bulan Ramadhan) [Ali Al-Shabuniy, Shafwaat
al-Tafaasir, juz III, hal.170.].
Ibnu Jaziy menyatakan, ”…al-Quran telah diturunkan pada Lailatul Qadar [ibid, hal. 170].”
Imam
Qurthubiy
berkata, …”Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang penuh keberkahan, sebab,
pada malam itu Allah Swt. menurunkan kepada hamba-Nya al-Quran al-Karim yang di
dalamnya berisi keberkahan, kebaikan dan pahala..” [Imam Qurthubiy, Tafsir
Qurthubiy, juz 16, hal.126.]
Imam Ibnu Katsir menyatakan, ”Allah
Swt. telah memuliakan bulan Ramadhan di antara bulan-bulan yang lain. Ini bisa
dimengerti karena bulan Ramadhan telah dipilih Allah Swt. untuk menurunkan
al-Qur'an al-Adzim. [Imam Ibnu
Katsir, Tafsiir Ibnu Katsiir: al-Baqarah [2]:
185]]
Dalam
riwayat-riwayat dituturkan bahwa
Ramadhan adalah bulan di mana Allah Swt. menurunkan kitab-kitabNya kepada para
Nabi.
Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu al-Asqa’ bahwa
Rasulullah Saw. berkata, “Shuhuf Ibraahim diturunkan pada malam pertama bulan
Ramadhan. Sedangkan Taurat diturunkan pada malam keenam bulan Ramadhan; Injil
diturunkan pada malam ketiga belas, dan al-Qur'an diturunkan pada malam keempat
belas bulan Ramadhan.” [HR. Imam Ahmad]
Dalam
sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Jabir bin ‘Abdullah disebutkan, ”Sesungguhnya
Zabur diturunkan pada malam kedua belas di bulan Ramadhan. Sedangkan Injil
diturunkan pada malam kedelapan belas Ramadhan.” [HR. Ibnu Mardawaih]
Yang dimaksud dengan al-Quran di sini
adalah al-Quran yang diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfudz ke langit
dunia (Baitul ‘Izzah). Setelah itu,
al-Qur'an diturunkan dari langit bumi kepada Nabi Muhammad Saw. secara
berangsur-angsur. [Lihat Imam Thabariy,
Tafsir Thabariy, Imam Qurthubiy, Tafsir Qurthubiy, dan Tafsir Jalalain.]
Al-Hafidz Suyuthi mengatakan, “Berkaitan
dengan firman Allah Swt. surat al-Baqarah : 185 dan al-Dukhaan :4, ada tiga
pendapat berbeda mengenai cara diturunkannya al-Quran dari Lauh al-Mahfudz.
Pendapat pertama –dan ini adalah pendapat yang paling shahih— menyatakan
bahwa al-Quran diturunkan dari Lauh al-Mahfudz ke langit dunia secara lengkap. Peristiwa
ini terjadi pada malam Lailatul Qadar (bulan Ramadhan). Setelah itu, al-Quran
diturunkan dari langit dunia kepada umat manusia secara berangsur-angsur selama
20 tahun, 23 tahun, atau 25 tahun sesuai dengan apa yang dilakukan oleh
Rasulullah Saw. setelah beliau diutus oleh Allah Swt…..” [al-Hafidz al-Suyuthi, al-Itqaan fi ‘Uluum al-Quran, hal 39. Al-Hafidz al-Suyuthi mengetengahkan
hadits-hadits yang mendukung pendapat ini, yakni hadits yang diriwayatkan oleh
al-Hakim, Baihaqiy, al-Nasaaiy dan lain-lain dari jalur Manshuur, dari Sa’id
bin Jabir, dari Ibnu ‘Abbas. Dalam
tafsir Jalalain disebutkan bahwa, al-Quran telah diturunkan dari Lauh
al-Mahfudz ke langit dunia (baitul ‘Izzah) pada Lailatul Qadar di bulan
Ramadlan.]
Ayat ini juga menjelaskan fungsi al-Quran
sebagai hudaan li al-naas (petunjuk bagi manusia), bayyinaat min
al-huda (penjelas), dan al-furqan (pemisah atau pembeda).
Imam Qurthubiy mengatakan, “Tafsir dari firman Allah Swt., “hudaan li
al-naas wa bayyinaat min al-hudaa wa al-furqaan” adalah sebagai berikut.
“Hudaa” dibaca nashab karena ia berkedudukan sebagai haal dari
al-Quraan. Susunan kalimat semacam ini bermakna, ”haadiyan lahum” [petunjuk
kepada mereka]. Sedangkan “wa bayyinaat” berkedudukan sebagai “‘athaf
‘alaih”. Arti ‘al-hudaa” sendiri adalah “al-irsyaad wa al-bayaan”
[petunjuk dan penjelasan]. Maknanya adalah, al-Quran dengan keseluruhannya,
baik ayat-ayat muhkaam, mutasyaabihaat, nasikh dan mansukh jika dikaji dan
diteliti secara mendalam akan menghasilkan hukum halal dan haram,
nasehat-nasehat serta hukum-hukum yang penuh hikmah”. Adapun “al-furqaan” bermakna “maa
farraqa bain al-haq wa al-baathil” [semua
hal yang bisa memisahkan antara yang haq dengan yang bathil]. [Imam Qurthubiy, Tafsir Qurthubiy, surat al-baqarah:185.]
Imam Thabariy menjelaskan bahwa ‘hudan
li al-naas” bermakna “rasyaadan
li al-naas ilaa sabiil al-haq wa qashd al-manhaj” [petunjuk kepada umat
manusia menuju jalan kebenaran dan metode yang lurus]. Adapun makna dari “bayyinaat
min al-hudaa” adalah “waadlihaat min al-hudaa” [petunjuk-petunjuk
yang sangat jelas]; artinya bagian dari petunjuk yang menjelaskan tentang hudud
Allah, faraaidhNya, serta halal dan haramNya. Sedangkan al-furqan berarti “al-fashl bain al-haq wa al-baathil” [pemisah
antara kebenaran dan kebathilan]. Makna ini sejalan dengan hadits yang
diriwayatkan dari al-Suddiy,
”Maksud
dari firman Allah Swt., “wa bayyinaat min al-hudaa wa al-furqaan” adalah
“bayyinaat min al-halaal wa al-haraam” [penjelasan yang menjelaskan halal
dan haram]. [Imam Thabariy, Tafsir
Thabariy, surat al-Baqarah : 185.]
Al-Hafidz al-Suyuthi dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa “al-hudaa”
bermakna “petunjuk yang dapat
menghindarkan seseorang dari kesesatan”. Sedangkan “bayyinaat min
al-hudaa” bermakna, “ayat-ayat yang sangat jelas serta hukum-hukum
yang menunjukkan seseorang kepada jalan yang benar’. Al-Furqaan sendiri
bermakna “pemisah antara kebenaran dan kebathilan”. [Al-Hafidz al-Suyuthiy, Tafsir Jalalain, surat al-baqarah:185.]
Menukil
pendapat Ibnu ‘Abbas, Fairuz Abadiy menyatakan,”Yang dimaksud
dengan firman Allah Swt. “hudaan li al-naas” adalah al-Quran itu berfungsi memberi petunjuk kepada manusia dari
kesesatan. Sedangkan frasa “wa bayyinaat min al-hudaa” bermakna
perkara-perkara agama yang sangat jelas dan tidak samar.” Adapun frasa “al-furqan” berarti halal dan haram, hukum-hukum dan hudud, serta
semua hal yang menghindarkan seseorang dari syubhat (kesamaran).” [Fairuz Abadiy, Tanwiir al-Maqbaas min Tafsiir Ibn ‘Abbas’, hal.20]
Ayat
di atas telah menggambarkan betapa Allah Swt. telah memulyakan dan mengagungkan
bulan Ramadhan di atas bulan-bulan yang lain. Sebab, di bulan itu Allah Swt.
menurunkan al-Quran yang berisikan petunjuk, penjelasan serta pemisah antara
yang haq dan bathil. Tidak hanya itu saja, al-Quran adalah sumber segala sumber
hukum bagi kaum muslim yang tidak boleh diingkari dan diacuhkan. Dalam masalah
ini Imam Ibnu Taimiyyah berkata:
“Barangsiapa
tidak mau membaca al-Quran berarti ia mengacuhkannya dan barangsiapa membaca
al-Quran namun tidak menghayati maknanya, maka berarti ia juga mengacuhkannya. Barangsiapa
yang membaca al-Quran dan telah menghayati maknanya akan tetapi ia tidak mau
mengamalkan isinya, maka ia pun berarti mengacuhkannya”.
Selanjutnya Imam Ibnu Taimiyyah menyitir sebuah
ayat:
“Berkatalah
Rasul: “Ya Tuhanku! Sesungguhnya kaumku menjadikan al-Quran ini suatu yang
diacuhkan.” [al-Furqan:30]
[Ali Al-Shabuniy, al-Tibyaan
fi ‘Uluum al-Quran]
Bunga Rampai
Pemikiran Islam